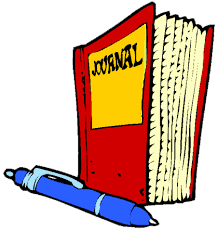Tembang “Ilir-Ilir”, dikenal oleh hampir sebagian besar masyarakat Jawa, masih menjadi misteri siapakah yang sebenarnya telah menggubahnya. Ada yang mengklaim, bahwa tembang itu gubahan Sunan Kalijaga, mengingat Sunan Kalijaga merupakan salah satu Walisanga yang selalu mengakulturasikan budaya Islam dan budaya Jawa sepanjang dakwahnya.
Tembang “Ilir-Ilir”, dikenal oleh hampir sebagian besar masyarakat Jawa, masih menjadi misteri siapakah yang sebenarnya telah menggubahnya. Ada yang mengklaim, bahwa tembang itu gubahan Sunan Kalijaga, mengingat Sunan Kalijaga merupakan salah satu Walisanga yang selalu mengakulturasikan budaya Islam dan budaya Jawa sepanjang dakwahnya.
Ada juga yang mengklaim, tembang itu gubahan Sunan Ampel, mertua Sunan Kalijaga dan sekaligus guru dan mertua Sunan Giri. Dan ada juga yang mengklaim, tembang itu merupakan tembang permainan hasil gubahan Sunan Giri, mengingat Sunan Giri adalah pendidik yang ahli dalam menciptakan tembang permainan anak-anak untuk kepentingan dakwahnya.
 Kesimpangsiuran siapa penggubah tembang “Ilir-Ilir” bisa dipahami, mengingat bahwa tembang ini merupakan sastra lisan (oral literature), sama kedudukannya dengan cerita rakyat (folklore), yang ditularkan dari mulut ke mulut. Terlebih, ketiga waliyullah itu tiga dari walisanga yang tidak menolak untuk menggunakan media kultural selama tidak menyimpangdari syariah Islam. Amat mungkin ketiga waliyullah itu pernah melagukan tembang tersebut pada tempat-tempat dan waktu-waktu dakwah yang berlainan. Dengan kenyataan ini, para santri atau pengikut para wali itu sama-sama meneruskan pemahaman bahwa tembang “Ilir-Ilir” telah digubah oleh Sunan Ampel atau Sunan kalijaga atau Sunan Giri. Terlebih lagi, yang merepotkan bagi pencatat sejarah adalah, tidak seorang pun dari tiga wali itu yang menyatakan telah menggubah tembang tersebut.
Kesimpangsiuran siapa penggubah tembang “Ilir-Ilir” bisa dipahami, mengingat bahwa tembang ini merupakan sastra lisan (oral literature), sama kedudukannya dengan cerita rakyat (folklore), yang ditularkan dari mulut ke mulut. Terlebih, ketiga waliyullah itu tiga dari walisanga yang tidak menolak untuk menggunakan media kultural selama tidak menyimpangdari syariah Islam. Amat mungkin ketiga waliyullah itu pernah melagukan tembang tersebut pada tempat-tempat dan waktu-waktu dakwah yang berlainan. Dengan kenyataan ini, para santri atau pengikut para wali itu sama-sama meneruskan pemahaman bahwa tembang “Ilir-Ilir” telah digubah oleh Sunan Ampel atau Sunan kalijaga atau Sunan Giri. Terlebih lagi, yang merepotkan bagi pencatat sejarah adalah, tidak seorang pun dari tiga wali itu yang menyatakan telah menggubah tembang tersebut.
Meski demikian, dalam tulisan ini, penulis lebih condong merujukkan tembang tersebut ke Sunan Giri. Alasannya, dalam sejarahnya Sunan Ampel bukan ahli dalam sastra, sementara Sunan Kalijaga dikenal masyhur menggunakan wayang sebagai media dakwah. Hal ini sejalan dengan penyelidikan Aminuddin Kasdi (2005: 45), bahwa untuk memikat hati rakyat Sunan Giri menciptakan tembang-tembang permainan (dolanan) yangmengandung ajaran dan jiwa keislaman, misalnya permainan jelungan, cublak-cublak suweng, ilir-ilir, bendi gerit, gula ganti dan sebagainya—di samping tembang macapat, kidung,asmaradana, dan pucung. Menurut Kasdi (2005, ibid), selain mudah dipahami, tembang dan kidung semacam itu sangat digemari rakyat karena berisi ajaran yang bertingkat tinggi.
Tulisan ini akan mencoba menafsirkan makna tembang “Ilir-Ilir” tersebut dengan pendekatan Kritik Sastra Pragmatik (Pragmatic Criticism), dan sekaligus mengungkapkan implikasinya. Dalam pendekatan kritik sastra ini, tembang tersebut diposisikan sebagai sebuah puisi Jawa dan akan ditafsirkan untuk menemukan maknanya, serta dikaitkan dengan nilai guna atau manfaat (utility) yang disumbangkan oleh tembang tersebut. Analisis diharapkan dapat menguak pendidikan moral, filsafat dan ketauhidan yang dikandungnya.
Pembahasan
Untuk memulai pembahasan ini, penulis tampilkan lirik-lirik tembang “Ilir-Ilir” Sunan Giri, sebagaimana dikutip oleh Kasdi (2005:45-46), dan sekaligus terjemahan bebas penulis ke dalam bahasa Indonesia, berikut ini:
Lirik Tembang Versi Bahasa Jawa
|
Lirik Tembang Versi Terjemahan (pen.)
|
Lir-ilir, lir-ilir
tandure wis sumilir sing ijo royo-royo tak sengguh penganten anyar
cah angon, cah angon
penekna blimbing kuwi lunyu-lunyu penekna kanggo mbasuh dodot ira
dodot ira, dodot ira
kumitir bedah ing pinggir dondomana jlumatana, kanggo seba mengko sore.
mumpung gede rembulane
mumpung jembar kalangane
yo soraka surak hore |
Yup-sayup mulai bangun
tanamannya t’lah tumbuh
yang hijau royo-royo
laksana pengantin baru
penggembala, penggembala
panjatkan blimbing itu
meski licin, panjatkan
‘tuk mencuci dodot-mu
dodotmu, dodotmu
tertiup [angin] sobek di pinggir
segera jahitlah, segera benahi
‘tuk ‘menghadap’ sore nanti
selagi terang rembulannya
selagi luas kalangannya
ayo sorak, sorak hore
|
Dalam tembang Jawa di atas, empat baris pertama merupakan ungkapan Sunan Giri tentang tanaman (Jw: tanduran); sedangkan baris-baris berikutnya tentang himbauannya kepada anak gembala atau penggembala (cah angon). Dilukiskanlah, sudahlah mulai bangun, benih yang pernah ditanam telah mulai tumbuh, tumbuh subur kehijauan, laksana sepasang pengantin baru. Selanjutnya, dihimbaulah sang penggembala untuk memanjatkan buah blimbing meski pohonnya licin, yang berguna untuk mencuci dodot (sejenis pakaian Jawa). Sementara itu, dodot itu, ketika dijemur, tertipu angin dan kelihatan sobek pinggirnya. Karena itu, penggembala diminta untuk menjahit dan membenahi, untuk ‘menghadap’ (sowan) pada sore nanti, selagi rembulannya masih terang dan masih luas kalangannya. Baris terakhir berupa ajakan untuk menyambut kegembiraan, dengan bersorak-sorai.
Tentu saja tembang itu tidak berhenti pada makna literal (harfiah) semacam itu. Mengapa? Sebagai sebuah tembang untuk berdakwah, tembang itu mengandung makna figuratif dan konotatif yang lebih dalam dan luas. Yang paling kentara adalah pemakaian simbolisasi dan personifikasi yang sarat makna.
Lir-ilir, lir-ilir
tandure wis sumilir
sing ijo royo-royo
tak sengguh penganten anyar
tandure wis sumilir
sing ijo royo-royo
tak sengguh penganten anyar
Lir-ilir mempersonifikasikan keadaan sesuatu atau seseorang yang baru bangun, yakni bangun dari tidur. Yang baru bangun, dalam konteks ini, adalah agama Islam dan para muallaf (pemeluk Islam yang baru). Mengapa demikian? Sebelum Sunan Giri menyebarkan agama Islam di Jawa, khususnya di daerah Gresik dan sekitarnya, masyarakat masih memeluk agama Hindu-Budha dan mengembangkan budaya berjiwa agama ini. Masyarakat masih tidur dan belum mengenal Islam; dan menganggap Islam sebagai agama yang asing. Dengan kehadiran Islam yang disebarkan oleh Sunan Giri, masyarakat secara perlahan namun pasti mulai sadar dan bangkit untuk memeluk Islam; mereka bisa diibaratkan ‘telah bangun (dari tidur)’. Islam dianggap sebagai agama yang menggugah kesadaran, dan membangunkan,.
Benih-benih ajaran Islam yang ditanamkan Sunan Giri sudah mulai tumbuh. Maksudnya, ajaran Islam telah mulai berhasil mengislamkan masyarakat sekitar Giri, yang dibuktikan oleh bertambahnya muallaf-muallaf yang mendalami dan menghayati Islam. Warna “hijau” menyimbolkan pertumbuhan yang subur dan sehat, tidak dimakan hama, dan pertumbuhannya pesat. Alangkah menyenangkan menyaksikan keadaan demikian. Keadaan yang menyenangkan dan menyejukkan itu bisa diibaratkan sebagai ‘pengantin baru’. Pengantin baru digunakan di sini untuk menggambarkan manusia yang enak dipandang, bahagia, penuh kasih sayang, dan siap menghadapi masa depan. Dengan demikian, para muallaf, jika diperhatikan, sangatlah menggembirakan hati Sunan Giri; karena mereka memancarkan kebahagiaan islami dan berperilaku islami setelah ‘tidur’ dalam agama-budaya Hindu-Budha meskipun pemahaman dan penghayatan agama mereka masih tergolong pemula.
Makna yang dapat dipetik dari bait pertama ini adalah, hendaknya setiap pribadi muslim (terlebih lagi para muallaf) itu bangkit dari ‘tidurnya’, bangkit dari ketaksadaran. Lalu mereka harus mengerjakan amal-amal saleh, agar iman dan Islamnya tumbuh subur dalam sanubari, sehingga dirinya disenangi orang banyak berkat akhlaknya yang terpuli dan mulia.
Sudah cukupkah kegembiraan Sunan Giri menyaksikan benih-benih ajaran Islam mulai bertumbuhan dengan subur? Jawabannya jelas, belum! Sunan Giri melanjutkan lirik tembangnya dengan sentilan bagi “penggembala” (cah angon) untuk memanjatkan “buah blimbing”.
cah angon, cah angon
penekna blimbing kuwi
penekna blimbing kuwi
Kata “penggembala” bisa dikonotasikan dengan pemimpin. Dalam sebuah Hadits disebutkan “Al-Imaamu Ro’in” (Imam adalah Pemimpin/Penggembala). Ro’in dalam bahasa Arab artinya (secara bahasa) penggembala dan secara urf (adat Arab) juga untuk menyebut sebagai pemimpin. Agaknya ungkapan ini dialamatkan ke para raja yang telah memeluk Islam, atau para santri Sunan Giri. Meski dalam Islam diyakini bahwa setiap manusia adalah pemimpin, dan akan bertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya, tampaknya ungkapan “cah angon” itu bukan untuk masyarakat kebanyakan, melainkan lebih menyempit pada para raja atau santri-santrinya. Mengapa? Ada kalimat “penekna blimbing kuwi” (panjatkan blimbing itu). Kata perintah “penekna” (panjatkan) bukan kalimat imperatif untuk memanjat untuk diri sendiri, melainkan juga untuk orang lain. (Jika untuk diri sendiri, kata yang digunakan tentunya “peneken”, panjatlah.)
Lalu, mengapa buah blimbing? Blimbing berwarna hijau (cirikhas Islam?) yang bersisi 5 (lima) digunakan untuk menyimbolkan lima rukun Islam, yakni: membaca syahadat, menegakkan shalat, membayar zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji jika sudah mampu. Perintah “penekna blimbing kuwi” (panjatkan blimbing itu) bisa dimaknai, para raja dan santri muallaf itu untuk mendalami dan mengamalkan rukun Islam dengan sebaik-baiknya. Secara lebih spesifik, blimbing berisi lima itu juga bisa dikonotasikan ke shalat lima waktu. Ini dengan alasan bahwa shalat merupakan tiang agama, dan dengan demikian merupakan inti sari rukun Islam yang lima itu. Seseorang yang mampu menegakkan shalat lima waktu, hakikatnya juga membimbingnya menunaikan kelima rukun Islam tersebut secara simultan, entah secara fisik saja maupun metafisik pula. Dan jika hal telah tercapai, para muslim(ah) menjadi peribadi yang patut diteladani. Karena itu, mereka harus melaksanakan rukun Islam untuk menunaikan tugas ketauhidan selanjutnya.
Begitulah, para raja dan santri muallaf itu, setelah menghayati Islam dengan baik, dapat bertindak sebagai pemimpin bagi diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Mereka harus mampu menjadi suri tauladan yang terbaik, untuk dapat memikat hati masyarakat yang belum memeluk Islam. Hal ini mengimplikasikan, bahwa para raja dan santri inilah yang ikut membantu menyiarkan agama Islam ke berbagai penjuru Gresik dan sekitarnya, dan bahkan ke kawasan yang lebih luas lagi di Jawa dan bahkan di luar Jawa. Inilah seruan para wali kepada para penguasa di Jawa, agar mereka bersedia mengambil (memeluk dengan sungguh-sungguh) Islam itu agar masyarakat bisa mengikuti langkahnya dan dengan itu aturan Islam dapat diterapkan ke masyarakat. Tidak mungkin Islam terterapkan secara keseluruhan (kaffah) tanpa ada kemauan penguasa “mengambil” Islam sebagai agama dan sistemnya. Dengan kata lain, tidak mungkin kiranya Sunan Giri hanya berdakwah sendirian, melainkan perlu disokong atau dibantu oleh para raja dan santrinya yang militant dan total dalam berjuang. Dengan pendekatan demikian, Islam diharapkan akan berkembang lebih pesat.
lunyu-lunyu penekna
kanggo mbasuh dodot ira
Begitu kuatnya harapan Sunan Giri agar para pemimpin menghayati Islam, sehingga beliau memotivasi mereka agar tetap menguatkan diri menghayati Islam, meski “licin” (lunyu-lunyu), berat, banyak kendala dan rintangan. Walaupun berat ujiannya, walaupun banyak rintangannya karena masuk agama Islam itu berkonsekwensi luas baik secara keluarga, sosial dan politik, maka tetap anutlah Islam untuk membersihkan aqidah dan menyucikan diri dari dosa dosa: “kanggo mbasuh dodot ira” (untuk mencuci dodotmu). Dalam budaya Jawa, dodot itu asesori pakaian (kemben) yang digunakan untuk menghadap raja atau ratu; yang harus dicuci bersih dan suci sebelum digunakan untuk menghadap (sowan) raja. Jika seseorang rakyat—yang di mata raja diposisikan sebagai hamba, kawula—menghadap raja dalam keadaan kotor dodotnya, maka dia akan dicap nistha (rendah), tidak etis, dan tidak tahu tata karma; sehingga mungkin saja dia tidak diijinkan menghadap.
Terkait simbol dodot, yang kotor itu, dapat disampaikan bahwa manusia memang berkecenderungan berbuat salah, khilaf, dan dosa. Ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa manusia, selain memiliki hati dan akal, juga memiliki nafsu (dalam berbagai bentuk dan wujudnya). Nafsu-lah yang mendorong untuk bertindak yang langsung atau tak langsung bersifat dosa. Meski demikian, manusia yang baik bukanlah manusia yang tanpa dosa sama sekali, karena tidak ada satu pun manusia yang imun dari dosa. Sebaliknya, manusia yang baik adalah manusia yang jika berdosa akan menebus dosanya dengan mencuci hatinya dengan perbuatan atau amal shalih. Mencuci dodot menyimbolkan adanya tindakan berbuat kebajikan untuk mencucikan diri dari kerak-kerak dosa yang melekati diri seseorang.
Dalam skala yang lebih luas, dodot juga menyimbolkan “ageman”atau sesuatu yang dikenakan, yang dalam hal ini agama Islam. Artinya, muallaf harus berusaha keras untuk menghayati agamanya yang baru, menyucikan diri dari agamanya yang terdahulu. Islam sebagai baru jangan sampai dicampuri dengan keyakinan dan ritual-ritual agama Hindu-Budha, sesuatu yang memang harus dibasuh, dicuci, dan dibersihkan ketika seorang muallaf mendalami Islam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya itu tentu saja harus disertai perjuangan yang tak kenal lelah.
Hal ini mengimplikasikan, bahwa menghayati Islam dengan sesungguhnya perlu perjuangan yang amat berat. Bahkan “lunyu-lunyu penekna” ini juga mengandung makna yang sangat dalam bagi setiap muslim, dalam membentuk jiwa yang kuat, pemberani, tanpa kenal lelah dan putus asa, sehingga akan membentuk pribadi-pribadi yang sabar, pantang menyerah demi sebuah cita-cita yang mulia. Apakah dampaknya? Tanpa disadari, menghayati Islam dengan sungguh-sungguh ini merupakan serangkaian laku bathin untuk mencuci diri dari segala khilaf dan dosa, terutama yang bersifat vertikal dengan Tuhan, tanpa mengesampingkan khilaf dan dosa terhadap sesama manusia. Mengapa demikian?
dodot ira, dodot ira
kumitir bedah ing pinggir
kumitir bedah ing pinggir
Ternyata dalam ranah individu, pakaian (dodot) manusia ada juga yang sobek sana-sini, artinya pakaian itu tidaklah utuh lagi. Yang mengetahui sobek-tidaknya dodot/pakaian itu, ternyata, bukan saja diri sendiri, melainkan orang lain. Dalam hal ini Sunan Giri, mendudukkan diri sebagai pesan lirik tembang, menyaksikan dodot/pakaian kita pembaca sedang sobek sana-sini. Sama dengan kotornya dodot/pakaian, sobeknya dodot/pakain tidak memungkinkan si pemakai mengenakannya untuk menghadap raja. Artinya, selain suci, dodot/pakaian harus dikondisikan untuk utuh atau tidak sobek pinggir-pinggirnya. Maknanya, selain dosa-dosa besar, manusia juga punya dosa-dosa kecil, tak terkecuali dosa yang berkaitan dengan manusia lain akibat bergaul dengan sesama manusia.
Bukan itu saja. Sangat boleh jadi dosa dan kesalahan manusia itu justru diakibatkan oleh belum diamalkannya ajaran Islam secara keseluruhan. Amalan keislamanannya masih bolong-bolong, belum secara keseluruhan, yang dalam praktiknya, misalnya, masih mencampur-adukkan dengan agama dan budaya Hindu-Budha. Kalau individu itu kebetulan seorang raja, maka selain sobek keyakinan dirinya, juga belum terislamakannya masyarakat, masih sobek sana-sini atau belum tersentuh. Hal ini memberikan gambaran, bahwa penghayatan para muallaf dalam ber-Islam belum sempurna, masih bolong, masih sobek pinggir keyakinannya.
Jika manusia masih belum sempurna hati dan perilakunya, juga ke-islaman-nya, maka haruslah diperbaiki, dengan cara dondomana, jlumatana (jahitlah,sulamlah, benahilah). Dengan disulam dan dibenahi, dodot itu akan patut dipergunakan untuk menemui orang yang dihormati, atau secara harafiah menghadap raja. Identik dengan itu, diri yang belum sempurna, juga keislamannya, haruslah ditingkatkan keimanan dan amalan shalihnya. Meningkatkan kualitas iman dan Islam tak beda jauh dengan menjahit dan membenahi pakaian yang sobek.
Itulah makna dari dondomana jlumatana artinya, jahitlah dan benahilah bagian yang sobek itu. Begitulah halnya dengan kepercayaan kita yang telah rusak, hendaknya kita berusaha bertobat dan mau memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan demikian, segala perbuatan yang sudah kita perbaiki tujuannya adalah sebagai bekal hidup di kehidupan akhirat kelak. Di sinilah letak makna dari kanggo seba mengko sore. Perjalanan manusia selama di dunia ini dengan mengikuti siklus hidup masing-masing—mulai dalam kandungan ibu hingga kematian (Hudson, 1996)—hanyalah sebagai persinggahan sementara, dari sebuah perjalanan panjang. Awalnya dia berangkat, kemudian kembali. Pagi dia kerja, sore sudah kembali. Sebelum pulang kembali di senja usia, keislaman dan keimanan diri harus dicuci atau disucikan sedemikian rupa agar diterima Sang Maha Raja.
Pengkaffahan keislaman dan penyempurnaan iman tentu harus ditempuh dengan mengamalkan rukun Islam dengan sebaik-baiknya, karena semua itu akan bermanfaat untuk menghadap Sang Maha Raja. Jadi, perbuatan yang baik seperti shalat, zakat, puasa, haji, sedekah dan lain sebagainya itu, tujuannya adalah sebagai bekal umat Islam untuk di menjalani kehidupan akhirat, dunia yang koindisinya hanya diketahui oleh Sang Maha Raja. Manusia tak punya kuasa apa-apa terhadapnya. Jangankan nasibnya di kehidupan akhirat, manusia sudah tak berdaya atas kuasa waktu, karena waktu telah mengalirkan dirinya dari bayi hingga masa tua, dua kutub ekstrem kehidupan manusia di dunia yang sebenarnya hanya nisbi belaka.
Karena itulah, setelah memberikan pesan bagi manusia untuk mencuci diri dan membenahi diri, Sunan Giri langsung menyambungnya dengan dua baris berikut ini:
mumpung gede rembulane
mumpung jembar kalangane
Selagi masih ada waktu, bersegeralah memperbaiki diri, mumpung terang sinar rembulannya, mumpung luas tempatnya berpijak dan bertindak, dan mumpung luas waktunya. Sebab, bila sudah malam hari tanpa sinar rembulan dan sempit ruang geraknya, orang tak akan dapat melihat apa-apa dan tak mampu melakukan apapun juga. Ini dimaksudkan, di saat gelap orang akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Acapkali yang baik dijelekkan, dan yang jelek dibagus-baguskan. Artinya, selagi masih muda, selagi sinar rembulan masih memancar, segeralah berbuat kebaikan, dan melaksanakan kewajiban yang telah diperintahkan. Digambarkan dalam sebuah Hadits, bahwa setiap muslim harus menjaga sempat sebelum sempitnya, jaga kaya sebelum miskinnya, jaga muda sebelum tuanya, jaga sehat sebelum sakitnya, dan jaga hidup sebelum matinya. Waktu yang ada, jangan disia-siakan tanpa guna dan berlalu begitu saja tanpa hasil yang signifikan.
Sementara itu, implikasinya bagi para raja dan santri-santri militan, Sunan Giri secara eufimistik mengingatkan, bahwa mereka pasti akan mati dan akan menemui Sang Maha Raja untuk mempertanggungjawabkan diri, keluarga dan masyarakat yang mereka pimpin. Maka mereka diminta untuk membenahi dan menyempurnakan keislaman dan keimanan masyarakat agar selamat di kemudian hari. Bukan itu saja. Sunan Giri juga mengingatkan agar para raja melaksanakan hal itu mumpung masih terbuka pintu hidayah menerima Islam dan masih banyak ulama-ulama yang bisa mendampingi beliau untuk memberikan nasehat dan arahan dalam menerima dan menerapkan Islam.
Mumpung si raja masih menduduki jabatan sebagai penguasa. Nanti perkaranya atau kesempatan melaksanakan ini akan hilang bila raja tersebut sudah tidak menjadi penguasa.
Kesempatan apa ? Usia atau pangkat/kedudukan ? Kalau yang dimaksud kesempatan adalah usia, maka ini kurang cocok. Bagaimanapun juga para wali juga tahu bahwa usia itu tidak bisa ditebak. Pangkat/kedudukan lebih masuk akal sebab masih bisa diduga kapan lengsernya .Bagi penulis “kalangan” bisa juga berarti pendukung sehingga maknanya juga bisa: mumpung selagi banyak pendukungnya, atau ruang gerak dalam pergaulan sosialnya. Bagian ini menjelaskan bahwa tembang ini adalah pesan para wali kepada raja raja agar raja memanfaatkan kesempatannya (sebagai raja) untuk, di samping masuk Islam, juga terlibat aktif dalam penyebaran dan pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya (tanah Jawa, Gresik).
Kesempatan apa ? Usia atau pangkat/kedudukan ? Kalau yang dimaksud kesempatan adalah usia, maka ini kurang cocok. Bagaimanapun juga para wali juga tahu bahwa usia itu tidak bisa ditebak. Pangkat/kedudukan lebih masuk akal sebab masih bisa diduga kapan lengsernya .Bagi penulis “kalangan” bisa juga berarti pendukung sehingga maknanya juga bisa: mumpung selagi banyak pendukungnya, atau ruang gerak dalam pergaulan sosialnya. Bagian ini menjelaskan bahwa tembang ini adalah pesan para wali kepada raja raja agar raja memanfaatkan kesempatannya (sebagai raja) untuk, di samping masuk Islam, juga terlibat aktif dalam penyebaran dan pelaksanaan syariat Islam di wilayahnya (tanah Jawa, Gresik).
Bila semua itu bisa dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka bergembiralah, dan sambutlah kemenangan. Yo surak’a, sorak hore. Kata ‘sorak’ adalah tanda perayaan kegembiraan, dan itu dilakukannya.kan untuk menyambut suatu keberhasilan yang telah diamalkannya. Logikanya, segala kewajiban yang dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka kehidupan di akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang baik pula. Karena itu, berbahagialah mereka yang mampu melaksanakan segala kewajiban dengan baik
Demikianlah, tembang Ilir-Ilir Sunan Giri memberikan pendidikan moral, filosofis, dan wejangan ketauhidan (ketuhanan)—serta politik dakwah, dengan melibatkan penguasa (umara). Kuatnya dampak positif tembang ini, dalam sejarahnya, tampak bagaimana sambutan masyarakat Giri dan daerah-daerah sekitarnya menghafalkan lirik tembang ini dengan baik pula. Bahkan ia dapat digolongkan sebagai salah satu karya sastra lisan yang penuh dengan simbolisme dan personifikasi yang kuat. Dihafalkannya oleh masyarakat tembang tersebut memberikan petunjuk seberapa hebat pengaruh Sunan Giri dalam syiar Islam, dan juga menunjukkan betapa bijaknya Sunan Giri dalam menyiarkan Islam kala itu, bahkan hingga mendekati masyarakat menggunakan tembang permainan sebagai produk kultural masyarakat Jawa; terlebih dalam budaya Jawa, ada kaitan erat antara manusia, dunia dan kosmos (Koentjaraningrat, 1994; Mulder, 1996).
Penutup
Berdasarkan pembahasan yangdipaparkan di atas dapatlah dikemukakan, bahwa tembang “Ilir-Ilir” Sunan Giri mengandung nilai pendidikan moral, filsafat, dan ketauhidan, dan bahkan politik dakwah. Sunan Giri sangat bijak dan mahir menyampaikan ajaran Islam dengan media tembang (sastra) selagi hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam menyampaikan isi, Sunan Giri telah menggunakan media yang pas, yakni tembang dolanan, yang dipastikan akan berguna untuk mendekati masyarakat Jawa yang kala itu masih beragama dan bersistem Hindu-Budha.
Penulis menggarisbawahi apa yang tersirat dalam suratan tembang ‘Ilir-Ilir’ tersebut, yang secara global mengandung setidaknya tidak hal. Pertama, bertutur tentang bangkitnya iman Islam. Kedua merupakan perintah untuk melaksanakan kelima rukun Islam semaksimal mungkin. Ketiga menganjurkan untuk tobat dan memperbaiki segala kesalahan yang telah dilakukan. Perbaikan itu diharapkan menjadi bekal untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Sedangkan bagian terakhir, mengajak umat untuk segera memperbaiki diri selagi masih ada kesempatan sebelum datang kesempitan, selagi sehat sebelum datang sakit, selagi mudah sebelum datang kesulitan, selagi muda sebelum datang tua, dan selagi hidup sebelum datang kematian.
Meski demikian, upaya penafsiran yang penulis lakukan hanyalah sekelumit upaya untuk memahami salah satu sisi kecil dari warisan Sunan Giri. Untuk memahaminya seluruh warisan Sunan Giri secara menyeluruh ibarat upaya menemukan mutiara-mutiara di dalam dasar samodera yang luas dan dalam, dan itu memerlukan pengetahuan dan penghayatan bathin yang memadai. Wallahu a’lam.
DAFTAR PUSTAKA
Kasdi, Aminuddin. 2005. Kepurbakalaan Sunan Giri, Sosok Akulturasi Kebudayaan Indonesia
Asli, Hindu-Budha, dan Islam Abad 15-16. Surabaya: Unesa University Press.
Hasyim, Umar. 1979. Sunan Giri dan Pemerintahan Ulama di Giri Kedaton. Kudus. Penerbit
“Menara” Kudus
Hudson, A.B. Siklus Hidup. 1996.Dalam T.O. Ihromi, ed. Pokok-Pokok Antropologi Budaya.
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
Mulder, Niels. 1996. Pribadi dan Masyarakat di Jawa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.